Faisol Fatawi || 5 Januari 2020
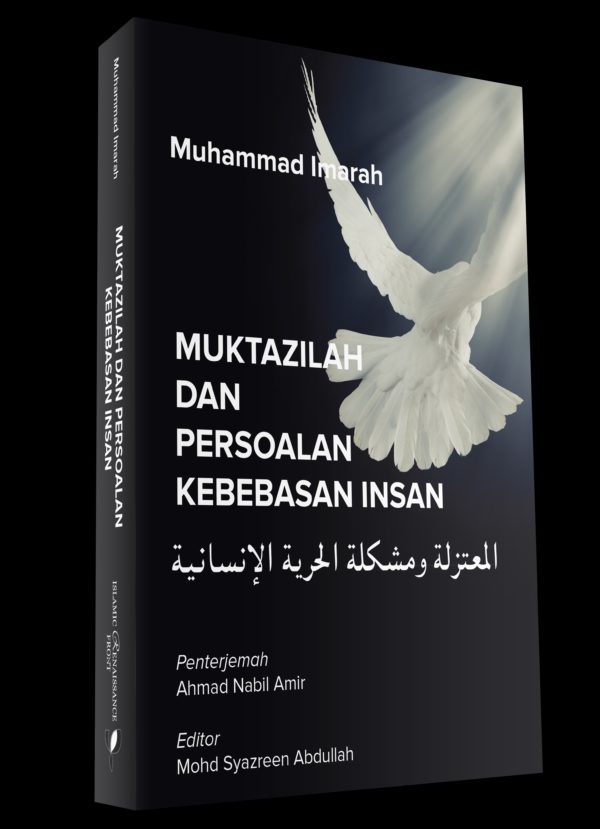 Munculnya diskusi tentang kebebasan berkehendak bagi manusia (hurriyat al-insan), tidak saja terkait dengan interpretasi terhadap teks al-Qur’an dan Hadith. Persoalan ini pertama kali muncul sebagai akibat dari peristiwa perselisihan politik pasca Rasulullah SAW, yaitu Majlis Tahkim yang berujung pada lahirnya aliran-aliran teologi dalam Islam. Masalah kebebasan berkehendak bagi manusia menjadi bagian dari salah satu isu yang diperdebatkan oleh setiap aliran dalam sejarah pemikiran teologi Islam.
Munculnya diskusi tentang kebebasan berkehendak bagi manusia (hurriyat al-insan), tidak saja terkait dengan interpretasi terhadap teks al-Qur’an dan Hadith. Persoalan ini pertama kali muncul sebagai akibat dari peristiwa perselisihan politik pasca Rasulullah SAW, yaitu Majlis Tahkim yang berujung pada lahirnya aliran-aliran teologi dalam Islam. Masalah kebebasan berkehendak bagi manusia menjadi bagian dari salah satu isu yang diperdebatkan oleh setiap aliran dalam sejarah pemikiran teologi Islam.
Sejarah pemikiran teologi Islam mencatat bahwa terdapat tiga gagasan besar dalam memahami dan menformulasikan masalah kehendak manusia. Pertama, bahwa manusia tidak memiliki kuasa (kehendak) dalam setiap aktifitas yang dilakukan. Setiap tingkah laku berasal dari Allah. Dengan kata lain, bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia adalah atas dasar dari kehendak Allah. Manusia dalam betindak tidak memiliki kebebasan karena semua apa yang mereka lakukan adalah berasal dari kehendak Allah; tidak memiliki kuasa atas kehendaknya sendiri. Arus pemikiran seperti ini kemudian dikenal dengan Jabariyah. Kedua, bahwa manusia makhluk yang bebas berkehendak. Tindakan yang dilakukan oleh manusia bukan atas dasar kehendak Allah. Manusia memiliki kuasa atas perbuatannya sendiri; manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Paham ini kemudian dikenal dengan sebutan qadariyah.
Di luar dua arus pemikiran tentang kehendak manusia itu, muncul pemikiran jalan tengah yang dimotori oleh Abu Hasan al-Asy’ari. Untuk keluar dari kedua aras pemikiran yang sangat ekstrim itu (Jabariyah dan Qadariyah), maka Al-Asy’ari mengajukan teori kasb, yaitu bahwa perbuatan manusia tidak mutlak berasal dari manusia sendiri, tetapi juga tidak mutlak dari Allah. Allah lah Dzat yang mewujudkan perbuatan manusia, tetapi manusia memiliki daya untuk mewujudkan perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, pada dasarnya Allah adalah fa’il (Pencipta) perbuatan manusia, tetapi manusia adalah kasib yaitu makhluk yang mengupayakan terwujudnya perbuatan itu melalui daya yang dimiliki. Manusia memiliki daya dan pilihan untuk mewujudkan perbuatan atas kehendak Allah.
Dalam tiga aras besar pemikiran tentang kebebasan berkehendak bagi manusia itu, Muktazilah mengambil jalan pemikiran kedua, yaitu bahwa manusia memiliki kehendak dan pilihan bebas dalam berbuat. Muktazilah mengambil sikap rasional dalam memahami masalah kehendak manusia. Sikap ini tidak dapat dipisahkan dari lima prinsip (al-ushul al-khamsah) yang mereka formulasikan untuk memahami persoalan teologi yang muncul ketika itu. Kelima prinsip itu adalah tauhid (al-tauhid), keadilan (al-adl), janji dan ancaman (al-wa’d wa al-wa’id), posisi antara dua posisi (al-manzilah bain al-manzilatain), dan amar ma’ruf nahi munkar (al-amr bi al-ma’ruf wa al-nah an al-munkar).
 Buku terjemahan yang ada di tangan pembaca ini mengulas persoalan kebebasan berkehendak bagi manusia (hurriyah al-insan) menurut Muktazilah. Setidaknya, kehadiran buku ini memberikan spirit rasionalisme bagi pembaca di tengah kuatnya arus kemajuan dan modernitas serta berbagai problematika yang dihadapi oleh umat Islam sekarang. Namun demikian, memotret pemikiran Muktazilah dan menghadirkannya kembali secara verbatim untuk konteks kekinian dalam menjawab problematika kemunduran yang dihadapi umat Islam, tentu tidak bijaksana dan kurang tepat. Karena diskursus pemikiran teologi Islam (khususnya yang dikembangkan oleh kaum Muktazilah) lahir dalam suatu konteks ruang dan waktu yang berbeda dengan konteks kekinian.
Buku terjemahan yang ada di tangan pembaca ini mengulas persoalan kebebasan berkehendak bagi manusia (hurriyah al-insan) menurut Muktazilah. Setidaknya, kehadiran buku ini memberikan spirit rasionalisme bagi pembaca di tengah kuatnya arus kemajuan dan modernitas serta berbagai problematika yang dihadapi oleh umat Islam sekarang. Namun demikian, memotret pemikiran Muktazilah dan menghadirkannya kembali secara verbatim untuk konteks kekinian dalam menjawab problematika kemunduran yang dihadapi umat Islam, tentu tidak bijaksana dan kurang tepat. Karena diskursus pemikiran teologi Islam (khususnya yang dikembangkan oleh kaum Muktazilah) lahir dalam suatu konteks ruang dan waktu yang berbeda dengan konteks kekinian.
Diskursus mengenai kebebasan berkehendak bagi manusia sebagaimana yang terjadi dalam sejarah pemikiran teologi Islam merupakan khazanah intelektual (al-turath) yang berharga. Hal itu menjadi potret bagaimana Islam berdialektika dengan konteks zamannya. Diskursus ini dapat dipandang sebagai upaya yang genuin dari para pemikir muslim dalam menjawab persoalan dan tantangan zaman yang mereka hadapi.
Masalah yang selalu dihadapi umat Islam di tengah warisan khazanah intelektual (al-turath) masa lalu, dalam menjawab tantangan kekinian adalah bagaimana seseorang harus berinteraksi dengan realitas; realitas kekinian (modernitas) dan masa lalu? Umat Islam memiliki masa lalu (teks suci, pernah mencapai titik puncak kemajuan peradaban-keilmuan, dan pengalaman-pengalaman yang lain) yang selalu dihadirkan. Tidak harus mengambil kembali khazanah masa lalu secara verbatim. Atau sebaliknya, membuang khazanah intelektual masa lalu karena alasan sama semakli tidak sesuai dengan konteks kekinia.
Dalam kaitannya dengan masa lalu, konteks kekinian, dan anggitan masa mendatang, seorang Muslim harus memiliki kemampuan membaca secara kritis. Menghadirkan kembali pemikiran Muktazilah dalam konteks sekarang, sebagaimana dalam buku ini, harus diletakkan dalam konteks pembacaan kritis itu. Dengan demikian, membaca secara kritis pemikiran Muktazilah bukan berarti kita takjub, menerima, dan mengulang konsep-konsepnya begitu saja. Tetapi, menelanjangi keterbatasan, kepentingan, dan ideologi yang bertenggar di dalamnya, serta menemukan aras-aras lain yang tidak dipikirkan dan terpikirkan olehnya, dan meletakkannya dalam konteks kekinian. Selamat membaca!
 Dr M. Faisol Fatawi adalah pensyarah di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Meraih gelar Doktor (Dr.) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015, pada konsentrasi Pemikiran Islam. Disertasi beliau berjudul “Naratologi al-Qur’an: Struktur dan Fungsi Naratif Kisah Nabi Musa dalam al-Qur’an”.
Dr M. Faisol Fatawi adalah pensyarah di Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Meraih gelar Doktor (Dr.) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015, pada konsentrasi Pemikiran Islam. Disertasi beliau berjudul “Naratologi al-Qur’an: Struktur dan Fungsi Naratif Kisah Nabi Musa dalam al-Qur’an”.

